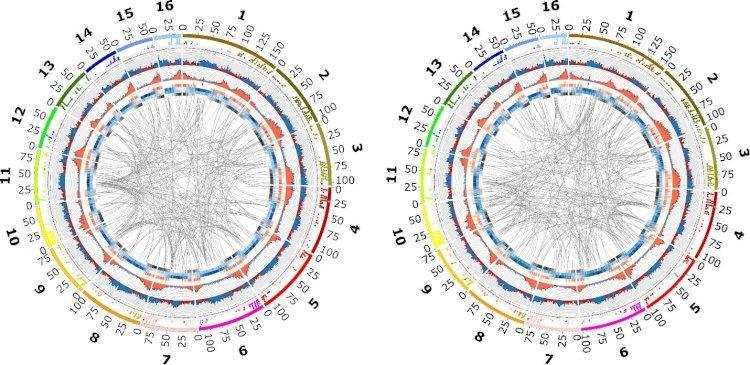Peta Kawasan Hutan Harus Akurat. Jika Tidak Hak Masyarakat Hilang

Jakarta, kabarsawit.com – Peta kawasan hutan yang beredar saat ini dinilai banyak pihak tidak akurat dan berpotensi merugikan masyarakat yang telah menguasai tanahnya secara sah.
Kepala Pusat Studi Sawit Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Budi Mulyanto, menegaskan bahwa kesalahan ini membuat hak-hak rakyat atas tanahnya hilang di mata hukum.
“Sayangnya, peta penetapan kawasan hutan saat ini belum sesuai dengan Undang-Undang. Banyak tanah yang sudah dikuasai masyarakat justru masuk ke dalam peta kawasan hutan. Ini seharusnya tidak terjadi,” ujar Prof. Budi dalam podcast @BungAA_cerita_kita.
Menurut Prof. Budi, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah menekankan perlindungan hak-hak masyarakat atas tanahnya.
Sejak pasal 13, undang-undang ini mengatur bahwa penguasaan masyarakat harus diinventarisasi dan dihargai, termasuk melalui Peraturan Pemerintah (PP) seperti PP 37/1998 yang mengatur legalitas penguasaan.
“Prinsipnya jelas, tanah yang dikuasai masyarakat, seperti lahan pertanian, kebun, atau permukiman desa, seharusnya tidak dikategorikan sebagai kawasan hutan. Tapi pada praktiknya, peta saat ini berskala kecil, 1 banding 500.000 atau bahkan 1 banding 50.000, sehingga detail bidang tanah masyarakat tidak terlihat,” jelasnya.
Prof. Budi menambahkan, kesalahan peta ini tidak hanya masalah administratif, tapi berimplikasi hukum. Banyak warga yang dianggap melanggar aturan kawasan hutan, padahal mereka memiliki hak legal atas tanahnya.
“Ini soal pengabaian. Peta yang ada sekarang belum detail, sehingga banyak masyarakat ‘terhapus’ haknya,” katanya.
Dalam penataan batas kawasan hutan, Prof. Budi menekankan pentingnya proses partisipatif. “Batas hutan harus ditentukan melalui kesepakatan semua pihak yang berbatasan. Tidak bisa ditentukan sepihak,” ujar Prof. Budi.
Menurutnya, proses verifikasi dan identifikasi harus dilakukan dengan skala peta yang lebih rinci agar bidang tanah masyarakat terlihat jelas dan hak mereka terlindungi.
Fenomena ini kerap muncul karena keterbatasan dana dan skala peta yang terlalu besar. “Prioritas penataan biasanya dilakukan pada batas luar terlebih dahulu, baru kemudian bagian dalam yang kompleks, termasuk lahan masyarakat,” tambahnya.
Prof. Budi menekankan bahwa sejak keluarnya peraturan Direktur Jenderal Kehutanan pada 1985, penataan hutan dan pengakuan tanah masyarakat sudah diatur secara lengkap.
Namun, praktik di lapangan seringkali melenceng. Banyak HGU (Hak Guna Usaha) atau lahan masyarakat masuk ke dalam kawasan hutan, sementara proses inventarisasi belum maksimal.
“Ini jelas masalah besar. Hukum sebenarnya menghargai hak masyarakat, tapi karena peta kawasan hutan salah besar, masyarakat dianggap melanggar. Akibatnya, hak rakyat hilang di mata hukum,” tegas Prof. Budi.
Dengan skala peta yang diperbaiki dan proses partisipatif yang tepat, hak masyarakat atas tanahnya bisa terlindungi, sekaligus pengelolaan hutan tetap berjalan sesuai fungsi ekologis dan sosial.
Prof. Budi menekankan bahwa pemerintah harus segera menindaklanjuti perbaikan peta dan verifikasi penguasaan masyarakat agar konflik lahan dan sengketa hak atas tanah bisa diminimalisir.
“Intinya, peta kawasan hutan harus akurat. Jika tidak, hak masyarakat hilang, dan pengelolaan hutan menjadi tidak adil,” tutup Prof. Budi.